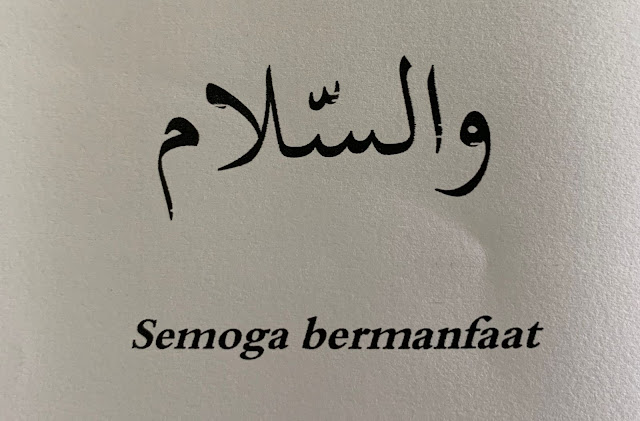Iman terbentuk dalam diri manusia diawali dari fitrah tauhid (menyembah Allah) yang Allah tanamkan dalam diri manusia sejak dia masih dalam rahim ibunya. Umumnya, fitrah ini akan tumbuh dalam diri manusia manakala lingkungan keluarga/sosialnya adalah Islam. Dalam kondisi semacam inilah Allah kemudian menurunkan hidayah kepada dia untuk beriman. Berikut ini penjelasannya.
Sabtu, 09 April 2022
Budaya Ramadhan 7 | Proses Terbentuknya Iman Dan Upaya Meningkatkannya
Iman terbentuk dalam diri manusia diawali dari fitrah tauhid (menyembah Allah) yang Allah tanamkan dalam diri manusia sejak dia masih dalam rahim ibunya. Umumnya, fitrah ini akan tumbuh dalam diri manusia manakala lingkungan keluarga/sosialnya adalah Islam. Dalam kondisi semacam inilah Allah kemudian menurunkan hidayah kepada dia untuk beriman. Berikut ini penjelasannya.
Budaya Ramadhan 6 | Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Perilaku Manusia dan Ikhtiar Merealisasikan Tugas Hidup Manusia
Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Perilaku Manusia
Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya sudah membawa potensi fitrah sejak lahir dan banyak memperoleh pengaruh dari lingkungannya, terutama lingkungan terdekatnya. Rasullah SAW bersabda.
“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orangtuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi” (H.R. Bukhori Juz 2 hal. 125).
Hadits tersebut menunjukkan betapa besar pengaruh orang- orang terdekat dalam hidup manusia. Saat ini pengaruh lingkungan di luar keluarga semakin banyak dan beragam, serta tidak hanya yang dekat, tapi yang jauh pun mudah sekali mendekat, seiring dengan era kemajuan sain dan teknologi. Hal-hal yang menguntungkan mudah sekali diakses dari jarak jauh, demikian juga halnya dengan hal-hal yang merugikan dan merusak moral.
Dalam bidang pendidikan dikenal beberapa aliran pendidikan, yaitu (1) Empirisme yang memandang perkembangan seseorang tergantung pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. (2) Nativisme yang berpandangan bahwa seseorang berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. (3) Naturalisme yang pandangannya dalam mendidik seseorang pendidik hendaknya kembali alam agar pembawaan seseorang yang baik tidak dirusak oleh pendidik. Terakhir (4) konvergensi yang memadukan aliran nativisme dan empirisme; perkembangan seseorang tergan- tung pada pembawaan dan lingkungannya. Dalam pandangan Islam, lama sebelum munculnya teori diatas, telah diterangkan bahwa tingkah laku manusia ditentutan oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan.
Dewasa ini pandangan yang banyak diikuti secara luas oleh para ahli adalah pandangan Islam, walaupun mereka menggunakan redaksi yang berbeda. Para ahli mengatakan bahwa secara garis besar ada 2 faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal adalah faktor yang datang dari diri individu, yang meliputi faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Faktor biologis atau struktur biologis meliputi struktur genetis, system syaraf dan sistem hormonal. Sedangkan faktor sosiopsikologis. Sebagai makhluk sosial, manusia mendapat beberapa karakter akibat proses sosialnya.
Faktor situasional adalah faktor dari luar individu, termasuk lingkungan. Kaum behavioris sangat percaya bahwa perilaku seseorang sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungannya. Menurut Islam prilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan tetapi juga oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan dapat berupa: faktor ekologis, faktor rancangan dan arsitektural, faktor temporal, suasana perilaku, tekhnologi, faktor-faktor sosial, lingkungan psikososial, stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka manusia dengan berbekal potensi-potensi (faktor personal) yang positif dan negatif yang berada pada dirinya berkewajiban untuk mencari ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Ilmu sangat berguna untuk mengembangkan potensi positif tersebut dan untuk mengurangi serta mengikis potensi negatif yang dimilikinya.
Ikhtiar Merealisasikan Tugas Hidup Manusia
Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa tugas manusia adalah menjadi khalifah di bumi. Tugas sebagai khalifah itu sejalan dengan firman Allah berikut.
“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S. al-Ahzab:72).
Tampak pada ayat tersebut bahwa di antara sekian banyak makhluk Allah manusialah yang bersedia mengemban amanat. Kesediaan mengemban amanat dari Allah tersebut mengandung suatu konsekuensi bahwa manusia harus lebih mengutamakan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah daripada menuntut hak. Karena itu istilah yang populer di dalam Islam adalah al-waajibaat wal huquuq “kewajiban dan hak” bukan sebaliknya, yaitu “hak dan kewajiban” sebagaimana yang populer di luar ajaran Islam.
Upaya merealisasikan tugas hidup tersebut harus dilakukan secara maksimal dan optimal sesuai kemampuan. Manusia hanya diberi kewenangan untuk berusaha, berhasil dan tidaknya usaha tersebut merupakan kewenangan Allah semata. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menyesali kegagalan suatu program yang sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik. Agar sukses dalam mengemban amanat sebagai khalifah, manusia dapat melaksanakan upaya-upaya berikut.
Pertama, berilmu yang memadai. Amanat menjadi khalifah akan dapat diemban manusia dengan baik apabila mereka memiliki ilmu yang memadai. Oleh karena itu, mencari ilmu merupakan keniscayaan bagi manusia, baik dalam kapasitasnya menjadi „abd Allah maupun khalifah Allah. Ibadah hanya akan diterima oleh Allah apabila dikerjakan sesuai ilmunya. Demikian juga dengan upaya memakmurkan bumi. Pemakmuran bumi akan berhasil dengan baik bahkan bernilai ibadah apabila dilakukan dengan sesuai ilmunya.
Kedua, bertindak secara nyata. Semua pihak harus melakukan tindakan nyata dalam pemakmuran dunia/bumi. Dalam konteks ini harus difahami bahwa tanggung jawab menjadi khalifah adalah tanggung jawab bersama. Manusia dengan statusnya masing-masing, misalnya „ulama’, umara’, aghniya’, fuqara’, berkewajiban untuk berkontribusi dan berkolaborasi menyukseskannya sesuai kapasitasnya masing-masing.
a. Para „ulama’ (ilmuwan) mengembangkan ilmunya, meneliti, mengadakan eksperimen, dan mensosialisasikan ilmu kepada pihak-pihak lain, utamanya kepada para umara’ (pejabat, teknokrat, karyawan, praktisi hukum, dan lain-lain) dan generasi penerus dengan mengajarkan ilmu tersebut atau dengan teknik sosialisasi yang lainnya.
b. Para umara’ melaksanakan tugas dan kewenangannya secara total dan adil. Dalam melaksakan tugas mereka harus sangat memperhatikan aspek-aspek dan prinsip-prinsip profesiona- litas, keseimbangan, kesinambungan, keselarasan, keuntungan bersama, tidak berlebihan, keramahan lingkungan, tanpa menimbulkan banyak efek negatif.
c. Para aghniya’ (hartawan) mendukung tugas umara’ dengan bantuan modalnya (membayar zakat, pajak, hibah, atau pinjaman modal kerja) untuk membiayai program-program pengembangan ilmu dan eksperimen yang dilakukan ulama‟, program-program pembangunan dan lainnya yang dilakukan oleh umara‟, dan pengentasan kemiskinan atau pemenuhan kebutuhan orang-orang miskin.
d. Kaum fuqara’ (fakir miskin) mendukung tugas ketiga unsur tersebut dengan doanya yang tiada henti.
Ketiga, mencari lingkungan yang baik. Menyadari akan besarnya pengaruh lingkungan dalam merealisasikan sesuatu yang diinginkan maka manusia harus mencari lingkungan yang kondusif.
Jika lingkungan kondusif tidak dapat diperoleh maka seseorang bisa menciptakannya. Ketika ingin memiliki ilmu yang luas, pemuda bisa datang ke pesantren, dan ketika Mekah sudah tidak kondusif untuk berdakwah, Rasulullah SAW hijrah ke Medinah.
Keempat, berdoa. Berdoa merupakan ciri khas orang yang beriman. Bagi mereka berdoa merupakan bagian yang terpisahkan dari usaha mengemban amanat dan dalam melaksanakan program apa saja. Tidak benar kalau ada orang yang berusaha hanya dengan bekerja tanpa berdoa dan tidak benar pula orang yang hanya berdoa tanpa berusaha nyata. Agar usaha dan doa tidak menyimpang dari aturan, maka bekal ilmu yang memadai menjadi syarat mutlak.
Kelima, menjaga hati. Sesuai dengan namanya hati cenderung tidak stabil. Oleh karena itu, hati harus dijaga agar selamat dari hal- hal yang menjadikannya labil dan sakit. Hati harus dijaga dari sifat- sifat yang tercela dengan cara mengarahkannya kepada sifat-sifat terpuji. Menjaga hati dilakukan dengan beribadah yang menurut al- Khawwash (dalam al-Qusyairi, tt juz 1 hal. 22) dinamakan dengan mengobati hati. Menurutnya obat hati itu ada lima, yaitu membaca al-Qur`an dengan menghayati maknanya, mengosongkan perut (berpuasa), melakukan salat malam, berzikir di keheningan malam, dan bergaul dengan orang-orang saleh.
Keenam, semua itu dilengkapi dengan bertawakal atau menyerahkan keberhasilan segala usaha dan jerih payah kepada Allah, Dzat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Orang yang beriman yakin bahwa manusia hanya memiliki kewenangan untuk berusaha, Allahlah yang berwenang menentukan berhasil atau gagalnya usaha tersebut. Namun patut dicatat bahwa usaha yang benar dan diniati dengan benar pula pastilah membuahkan keuntungan yang berupa pahala. Orang yang berijtihad lalu hasilnya benar maka ia mendapatkan dua pahala dan jika tidak benar maka ia mendapatkan satu pahala. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada usaha orang beriman yang sia-sia.
Jumat, 08 April 2022
Budaya Ramadhan 5 | Memahami Potensi Positif Dan Negatif Manusia
Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia dibekali potensi yang dapat dimanfaatkannya dalam menjalani kehidupannya menuju ke arah positif atau negatif yang dicita-citakannya. Namun Allah telah memberi petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan ia juga diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Allah berfirman:
“Dan (demi) jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”( Q.S. al-Syams:7-10).
“Siapa yang hendak beriman, silahkan beriman. Siapa yang hendak kafir silahkan juga kafir” (Q.S. al-Kahfi:29).
Penjelasan al-Qur`an tentang potensi positif dan negatif yang ada pada diri manusia tidak berarti menunjukkan adanya perten- tangan satu dengan lainnya, akan tetapi untuk menunjukkan beberapa kelemahan manusia yang harus dihindari. Disamping itu untuk menunjukkan pula bahwa manusia memiliki potensi untuk
menempati tempat tertinggi sehingga ia terpuji, atau berada di tempat yang rendah, sehingga ia tercela (Shihab, 1996:282).
Tim Dosen PAI UM (2011:40-41), menyebutkan potensi positif dan negatif manusia yang diterangkan di dalam al-Qur‟an, antara lain, meliputi:
a. Potensi positif, diantaranya:
1) Manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah (Q.S. al-Rum:30).
2) Manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik- baiknya (Q.S. al-Tin:5).
3) Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia (Q.S. al- Isra‟:70)
4) Manusia adalah makhluk Allah yang terpintar (Q.S. al- Baqarah:31-33, al-Naml:38-40)
5) Manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanat (Q.S. al-Ahzab:72)
b. Potensi negatif, antara lain:
1) Manusia adalah makhluk yang lemah (Q.S. al-Nisa‟:28)
2) Manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah (Q.S. al- Ma‟arij:19)
3) Manusia adalah makhluk zalim dan ingkar ( Q.S. Ibrahim:34)
4) Manusia adalah makhluk yang suka membantah (Q.S. al- Kahfi:54)
5) Manusia adalah makhluk yang suka melewati batas (Q.S. al- Alaq:6-7) dan lain lain.
Lebih lanjut TIM Dosen PAI UM (2011: 41—45) mengemu- kakan bahwa potensi positif atau negatif manusia dapat diketahui melalui uraian tentang fitrah, nafsu, qalb dan akal, sebagai berikut.
1. Fitrah
Fitrah diartikan sebagai penciptaan atau kejadian. Ini berarti bahwa fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak lahir yang merupakan penciptaan Allah. Q.S. al-Rum:30 menyebutkan fitrah manusia itu.
“Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama (pilihan) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.”
Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sejak awal kejadiannya membawa potensi agama yang lurus (tauhid) dan tidak dapat menghindari dari fitrah itu. Ini berarti bahwa fitrah keaga- maan akan tetap melekat pada diri manusia untuk selamalamanya. Dengan kata lain manusia menurut fitrahnya adalah makhluk beragama (mempercayai keesaan Tuhan). Apabila ini dipelihara dan dikembangkan, maka seseorang akan dapat mewujudkkan potensinya ke arah yang positif. Namun tidak sedikit di antara manusia yang ternyata mengabaikannya, sehingga membuat dirinya cenderung ke arah yang negatif.
2. Nafs (Nafsu atau Jiwa)
Nafs dapat diartikan sebagai syahwat (nafsu) dan juga dapat diartikan sebagai jiwa. Secara umum dapat dikatakan bahwa nafs menunjuk kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk, yang diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan berfungsi menampung dan mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan (Shihab, 1996:286). Dalam hal ini, al-Qur`an melalui surat al-Syams:7-10 menganjurkan untuk memberi perhatian yang besar pada nafs. Melalui ayat ini Allah mengil-hamkan kepada manusia melalui nafs, agar dapat menangkap kebaikan dan keburukan, serta mendorong manusia untuk menyucikan nafs.
Nafs yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dinamakan nafs al-mutmainnah, sedangkan yang mendorong untuk melakukan keburukan dinamakan nafs al-lawwamah. Para kaum sufi mengatakan bahwa nafsu adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk, yang mendorong manusia berbuat jahat (Q.S. Yusuf:53). Apabila nafsu itu diperturutkan maka akan merusak segalanya (Q.S. al-Mukminun:71). Allah akan mencabut iman dari diri seseorang yang menuruti hawa nafsunya untuk berzina dan minum khamr.
“Barangsiapa berzina atau minum-minuman keras, Allah mencabut daripadanya akan iman, seperti melepaskan seseorang akan bajunya dari kepalanya” (HR. al- Hakim juz 1 hal. 72).
Pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat dari potensi negatifnya, namun daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik kebaikan. Karenanya manusia dituntut untuk memelihara kesucian nafsu dan tidak mengotorinya (Q.S. al-Syams:9-10). Dengan kata lain Islam tidak menganjurkan untuk membunuh nafsu, melainkan mengendalikan dan mengolahnya serta mengarahkannya kepada nilai-nilai yang mempertinggi derajat kemanusiaanya.
Bagaimanapun juga nafsu tetap dibutuhkan manusia, sebab kalau nafsu tersebut dibunuh sehingga manusia tidak lagi memiliki nafsu (seperti nafsu makan dan nafsu syahwat), maka akan menyebabkan manusia tidak bisa bertahan hidup dan akhirnya akan musnah.
3. Qalb (hati)
Pada umumnya orang mengartikan qalb itu sebagai hati. Secara bahasa, qalb bermakna membalik, karena sering kali berbolak-balik, terkadang senang, terkadang susah, ada kalanya setuju, ada kalanya menolak. Dengan demikian qalb berpotensi tidak konsisten, ada yang baik ada pula sebaliknya. Baik atau buruknya sifat seseorang sangat ditentukan oleh qalbnya. Rasulullah SAW bersabda:
“Sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Apabila (segumpal daging itu) baik, maka baiklah seluruh dirinya. Dan apabila buruk, maka buruklah seluruh dirinya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalb (hati).” (H.R. Bukhori juz 1 hal. 20).
Qalb atau hati yang baik akan memberi pengaruh kepada sifat- sifat seseorang untuk melakukan tindakan yang terpuji, yang disebut al-qolb al-salim atau al-qalb al-nurany. Ini terjadi jika orang tersebut menghiasi hatinya dengan kekuatan iman dan sifat terbaik yang selalu berada dalam ridha Allah. Kalau demikian halnya ia akan dapat mewujudkan kebaikan dalam hidupnya, sehingga ia akan merasakan hidup yang bahagia, tenang, dan sejahtera.
Sebaliknya apabila qalb itu buruk, akan menghasilkan sifat-sifat yang tidak terpuji. Manusia yang hatinya demikian akan memperturutkan ajakan nafsu dan bisikan syetan, sehingga hatinya menjadi busuk dan kotor, penuh dengan penyakit. Ia tidak mampu menerima hidayah Allah, akibatnya dengan mudahnya ia melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Ilahi dan berbuat dosa. Hal ini akan mencelakakan dirinya, karena ia akan merasakan kesengsaraan dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.
Dari uraian di atas tampak dengan jelas, bahwa qalb (hati) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu hati harus terus dirawat dan dipelihara serta dihindarkan dari penyakit yang dapat menyengsarakan hidup. Harus ada usaha untuk menjaga kebersihan dan kejernihan hati agar senantiasa berada di bawah ridha dan naungan Ilahi.
4. Aql (akal)
Menurut Quraish Shihab (1996:294), aql atau akal diartikan sebagai pengikat, penghalang. Maksudnya ialah sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa. Selanjutnya akal dapat dipahami antara lain sebagai:
1) Daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu (Q.S. al- Ankabut:43).
2) Dorongan moral.
Dorongan moral tidak lain merupakan potensi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan atau dilarang oleh agama.
3) Daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah.
Dengan daya ini manusia memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisis dan menyimpulkan berdasarkan dorongan moral yang disertai kematangan berpikir.
Manusia harus mampu menggabungkan kemampuan berpikir dengan dorongan moral agar apa yang ia lakukan dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Sebab, apabila ia tidak mampu menggabungkan keduanya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya, terutama jika dorongan moral itu diabaikan. Bila ini terjadi, dengan mudahnya orang tersebut akan melakukan perbuatan yang menyimpang, yang berakibat dosa dan merugikan dirinya sendiri, karena ia akan menjadi penghuni neraka (Q.S. al-Mulk:10).
Budaya Ramadhan 4 | Kedudukan Dan Tujuan Penciptaan Manusia
1. Kedudukan dan Tugas Hidup Manusia
Dalam pandangan Islam, manusia diberi dua kedudukan yang mulia oleh Allah, yaitu sebagai hamba Allah (‘abdullah) dan khalifah Allah. Sebagai hamba Allah, manusia bertugas beribadah serta tunduk dan patuh kepada-Nya. Keharusan beribadah, tunduk, patuh, serta menyembah Allah antara lain berdasarkan firman Allah SWT berikut.
“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku” (Q.S. Thaha:14).
Semua manusia adalah abdullah, termasuk para nabi. Atha‟ bin Yasar pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Ash r.a: “Beritahulah saya tentang sifat Rasulullah SAW di dalam kitab Taurat!” Abdullah berkata:
“Tentu, Demi Allah, sesungguhnya beliau di dalam kitab Taurat disifati dengan sebagian sifat yang terdapat di dalam Al-Qur‟an; wahai Nabi sesungguhnya saya mengutusmu sebagai saksi, penyampai berita gembira dan berita yang menakutkan, penolong bagi kaum yang buta huruf. Engkau adalah hambaku dan utusanku. Saya menamaimu „almutawakkil‟ bukan orang yang keras kepala dan berhati kasar” (H.R. Bukhori, di dalam Fath al-Bari juz 2: 87).
Abdun dalam hadis tersebut ditujukan kepada Rasulullah SAW, namun tidak hanya digunakan untuk beliau tetapi digunakan pula untuk hamba Allah yang lain, baik para nabi dan rasul maupun manusia biasa, bahkan untuk makhluk lain selain manusia. Secara leksikal makhluk yang menyembah Allah dinamakan ‘abid’ sedang- kan Allah disebut Ma’bud atau Dzat Yang Disembah.
Kedudukan manusia itu unik. Ia berada di antara malaikat dan binatang. Ia bisa naik ke kedudukan yang sama dengan malaikat apabila bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dibanding malaikat. Rasulullah adalah manusia yang berhasil menembus tempat yang tidak mampu ditembus malaikat, yaitu Sidrat al-Muntaha dan Mustawa. Sebaliknya manusia akan turun derajatnya ke derajat binatang apabila ia menuruti hawa nafsunya. Bahkan mereka bisa lebih rendah daripada binatang, sebagaimana yang disebutkan di dalam QS. Al- A‟raf:179 dan al-Furqan:44.
Selain sebagai abdullah, manusia juga berkedudukan sebagai khalifah (wakil atau pengganti) Allah yang merujuk pada tugasnya sebagai pemegang mandat Tuhan guna mewujudkan kemakmuran di bumi. Di dalam al-Qur`an kata khalifah disebutkan dua kali, yaitu:
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (Q.S. Al-Baqarah:30).
Al-Shabuny (1976:I/48) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat tersebut adalah makhluk yang mewakili atau menggantikan Allah di dalam mengelola hukum-hukum Allah di bumi. Menurut Al-Jilany (2009:62) tugas kekhalifahan itu adalah memperbaiki akhlak dan hal-ihwal penghuni bumi. Makhluk tersebut sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat berikutnya adalah nabi Adam dan keturunannya. Mereka dicipta oleh Allah untuk menjadi pengganti makhluk yang mendiami bumi sebelumnya, yang dalam banyak kitab tafsir disebut banu al-jan (anak-cucu jin).
“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (Q.S. Shaad: 26).
Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Nabi Dawud oleh Allah dijadikan sebagai khalifah. Bila dipadukan dengan ayat 30 surat al- Baqarah, maka Nabi Dawud bukanlah satu-satunya manusia yang diangkat menjadi khalifah. Namun semua manusia juga dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi khalifah.
Dengan demikian jelas bahwa manusia dalam hidupnya memiliki tugas sebagai ‘khalifah fi al-ardhi’ atau penguasa di bumi. Artinya, manusia menjadi penguasa untuk mengelola dan mengendalikan segala apa yang ada di bumi (yang dalam al-Qur`an disebut dengan al-taskhir) untuk kemakmuran dan ketenteraman hidupnya, dalam bentuk pemanfaatan (al-intifa’), pengambilan contoh (al-i’tibar), dan pemeliharaan (al-ihtifadz) (TIM Dosen PAI UM, 2011: 49-50).
Merujuk pada makna kata khalifah yang diartikan sebagai wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan, ini berarti kekuasaan yang dipegang manusia hanya semata-mata memegang mandat Allah (mandataris). Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, manusia harus selalu mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang memberi mandat. Apa yang dikerjakan oleh manusia dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, Sang Pemberi Mandat tersebut (Nurdin, et. al., 1993:15). Aturan-aturan itu berupa hukum Tuhan yang dibuat sedemikian rupa, agar manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahannya selalu mendapatkan ridla Allah, sehingga ia bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat .
Dalam memakmurkan bumi ini, manusia harus selalu mengerjakannya atas nama Allah (bism Allah), yakni disertai tanggung jawab penuh kepada Allah dengan mengikuti „pesan‟ dalam mandat yang diberikan kepadanya. Kelak di akhirat pada saat menghadap Allah, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kinerjanya dalam menjalankan mandat sebagai khalifah-Nya di muka bumi (Madjid, 2000:157). Itulah sebabnya apabila manusia melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan tersebut, ia akan mendapatkan sangsi, yaitu kesulitan dan keseng-saraan hidup di dunia, dan siksa yang amat pedih di akhirat.
Secara potensial, manusia memiliki potensi dan kesanggupan yang signifikan untuk menjalankan tugas kepemimpinannya di bumi, karena dia tercipta dari unsur tanah. Begitu juga sebelum manusia menjalankan tugasnya, Allah telah memberi bekal dengan mengajarkan nama-nama segala benda yang ada di bumi dan tidak satu pun dari malaikat yang mengetahuinya (Q.S. al-Baqarah:31-33). Hal ini juga berarti bahwa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia terlebih dulu dituntut mengenali berbagai persoalan tentang bumi. Hal ini agar dalam menjalankan tugasnya manusia tidak merasa asing, tetapi betul-betul sudah dalam keadaan siap.
2. Tujuan Penciptaan Manusia
Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia atau tanpa maksud. Itulah sebabnya manusia diperintahkan Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaan tersebut (Q.S. Ali Imran:191). Tujuan penciptaan manusia harus difahami dengan seksama agar manusia berupaya melakukan apapun yang dikehendaki Allah dan
tidak menyimpang dari ketentuan-Nya. Menurut al-Qur‟an, Allah menciptakan manusia agar ia beribadah kepada-Nya.
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan” (Q.S. al- Dzariyat:56-57).
Dalam konteks ini, beribadah berarti mengabdi, berbakti, dan menghambakan diri kepada Allah SWT. Istilah “beribadah” tidak boleh diartikan secara sempit seperti pengertian yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, yakni terbatas pada aspek ritual seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Akan tetapi “beribadah” harus diartikan secara luas, yaitu meliputi ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan atas ketentuan dan kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dalam menjalani hidup di bumi ini, baik yang menyangkut hubungan vertikal (manusia dengan Allah) maupun hubungan horisontal (manusia dengan manusia dan alam sekitar), atau yang lebih dikenal dengan istilah habl min Allah wa habl min al-nas yang diwujudkan dalam bentuk iman dan amal saleh.
Dalam beribadah, manusia harus memperhatikan kehalalan makanan dan minuman serta fasilitas yang digunakan dalam menjalankan ibadah. Sebab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dinyatakan ada orang yang tekun dan sungguh-sungguh memohon kepada Allah hingga pakaiannya compang camping, rambutnya awut-awutan, namun karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya didapat dari cara yang haram, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah.
Ibadah, walaupun perintah Allah namun harus disikapi sebagai fasilitas bukan sebagai beban. Sebab jika ibadah dikerjakan maka pelakunya akan memperoleh dua hal sekaligus, yaitu ampunan dari dosa yang pernah ia kerjakan dan memperoleh tambahan pahala (poin) untuk kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Kalau manusia tidak mau beribadah, maka yang rugi adalah dirinya sendiri, tidak sedikitpun merugikan Allah, karena meskipun seandainya seluruh manusia tidak beribadah kepada Allah maka tidak akan sedikitpun mengurangi kekuasaan Allah, demikian pula sebaliknya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman:
“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu membuat-Ku merugi dan tidak akan mampu membuat-Ku beruntung. Wahai hamba-Ku, andaikata manusia dan jin mulai generasi pertama sampai generasi terakhir semuanya mencapai tingkatan tertinggi dalam ketaqwaan, maka yang demikian itu tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikitpun. Wahai hamba-Ku, andaikata manusia dan jin mulai generasi pertama sampai generasi terakhir semuanya mencapai tingkatan terbesar dalam berbuat dosa, maka yang demikian itu tidak akan mengurangi kekuasaan-Ku sedikitpun” (H.R. Muslim Juz 8 Hal. 16).
Budaya Ramadhan 3 | Hakikat Manusia
A. Hakikat Manusia
Jika manusia ingin mengetahui secara pasti mengenai hakikat dirinya secara benar, maka ia harus kembali ke Penciptanya melalui pemahaman dan penyelidikan terhadap firman-firman-Nya (al- Qur`an dan hadis). Hal ini sangat beralasan karena al-Qur`an merupakan kitab suci terlengkap yang diturunkan Allah ke bumi. Kandungannya meliputi segala aspek kehidupan.
Di dalam al-Qur`an telah dijelaskan gambaran konkret tentang manusia, dan penyebutan nama manusia tidak hanya satu macam. Azra dkk. (2002: 3/161) mengemukakan bahwa di dalam Al-Qur`an ada tiga istilah untuk manusia: al-basyar, al-nas, dan al-ins atau al- insan. Sedangkan Depag RI (1999: 10—11) menyebutkan lima istilah untuk manusia, yaitu bani Adam, basyar, nas, insan, dan ‘abd. Penyebutan ini untuk menunjukkan berbagai aspek kehidupan manusia itu sendiri, yaitu antara lain:
Sebutan Bani Adam bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis, karena manusia adalah Bani Adam, “anak-cucu Adam”. Silsilah manusia semuanya berhulu dari Nabi Adam AS. Allah SWT berfirman:
“Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu" (Q.S. Yasin:60).
“Tuhan yang membaguskan tiap-tiap sesuatu yang Ia jadikan. Dan Ia mulai membuat manusia dari tanah, kemudian Ia jadikan turunannya itu dari sari pati dan air yang hina.” (Q.S. al-Sajdah:7-8).
Dalam kedua ayat tersebut dikemukakan bahwa manusia mula- mula (manusia pertama) diciptakan dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang satu rupa. Setelah sempurna Allah meniupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah manusia, yang tidak lain adalah Adam. Manusia berikutnya (keturunan Adam) diciptakan oleh Allah dari sari pati dan air yang hina.
1. Manusia disebut basyar berdasarkan tinjauan secara biologis, yang mencerminkan sifat fisik-kimiawi-biologisnya. Penyebutan kata basyar di dalam Al-Qur`an tidak kurang dari 35 kali, di antaranya adalah:
“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak” (Q.S. al- Rum:20).
Kata basyar pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah, kemudian lahir kata basyarah yang berarti kulit. Jadi, istilah basyar ini untuk menunjuk bahwa kulit manusia tampak jelas dan berbeda dari kulit hewan (Shihab, 1996:279).
2. Manusia disebut insan berdasarkan tinjauan secara intelektual, yakni makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. Penyebutan kata insan di dalam Al- Qur`an tidak kurang dari 58 kali, di antaranya adalah:
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik- baiknya” (Q.S. al-Tin:4).
“Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara” (Q.S. al-Rahman:3- 4).
3. Secara sosiologis manusia disebut nas, yang menunjukkan kecenderungannya untuk berkelompok dengan sesama jenisnya. Allah SWT berfirman:
“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal-mengenal ” (Q.S. al-Hujurat:13).
Kecenderungan berkelompok tersebut menjadikan manusia berusaha mengenal satu sama lain, lalu mereka hidup berdam- pingan, dan saling membantu dalam komunitasnya. Tidak hanya itu, mereka juga saling menjalin persaudaraan baik dalam bentuk persaudaraan senasab, ukhuwwah islamiyyah (persaudaraan antarsesama muslim), ukhuwwah wathaniyah (persaudaraan antar warga bangsa).
Penulis tidak memasukkan abd sebagai salah satu penyebutan untuk manusia, sebab abd yang artinya hamba berlaku juga untuk makhluk lain yang diperintahkan melakukan ibadah, misalnya jin.
Budaya Ramadhan 2 | Perbandingan Agama
A. Perbandingan Agama (Muqaranah Al-Adyan)
1. Yahudi
Yahudi adalah agama tertua di antara agama-agama Semitik (Ibrahimiah). Agama ini telah hidup hampir 4000 tahun dalam periode-periode yang ditandai oleh perubahan, baik yang evolu- sioner maupun revolusioner. Meskipun penyebar sebenarnya agama Yahudi adalah Nabi Musa AS, orang Yahudi ortodoks memandang bahwa agama mereka itu bermula dari Nabi Ibrahim AS, nenek moyang mereka. Ibrahim AS adalah Bapak Monoteisme, karena ia adalah pioner tradisi monoteistik yang diikuti oleh keturunannya dan banyak bangsa di dunia ini.
Tradisi monoteistik yang diperjuangkan Ibrahim AS dan keturunannya (Ishaq AS, Ya‟qub AS, dan seterusnya) mendapat tantangan dari kepercayaan kafir dan syirik. Suku-suku bangsa lain tetap menyembah Tuhan-Tuhan mereka sendiri. Suku-suku bangsa Kanaan mempunyai Baal-Baal; orang Mesir mempunyai Ra, Osiris, dan Amon; dan orang Aegea masih mempunyai Tuhan-Tuhan lain. Agama Israil pada masa itu dirusak oleh kepercayaan animisme, penyembahan nenek moyang, sihir, dan kepercayaan terhadap Tuhan-Tuhan antropomorfis (jelmaan).
Dalam situasi krisis sosial dan keagamaan itu, lahirlah seorang bayi Israil di Mesir yang diberi nama Musa. Bayi yang selamat dari pembunuhan yang diperintahkan oleh Fir‟aun (Ramses II, berkuasa sekitar 1279 - 1212 SM) itu kelak menjadi pemimpin besar Yahudi yang berjuang membebaskan mereka dari kekejaman Fir‟aun. Tokoh yang hidup pada abad ke-13 SM itu adalah pahlawan pembebasan dan bapak yang sebenarnya dari orang Yahudi. Bila inspirasi monoteistik asli datang dari Nabi Ibrahim AS, maka Nabi Musa AS adalah orang yang membuka, menetapkan, dan mengukuhkan pandangan hidup keagamaan itu.
Nabi Musa AS tidak hanya memimpin pembebasan Israil keluar dari perbudakan Fir‟aun dan bangsa Mesir, tetapi ia juga membawa mereka kepada perjanjian dengan Tuhan mereka, yaitu Yahweh di Gurun Sinai. Di gurun itu, ia menerima Sepuluh Perintah (Ten Commandments) dari Tuhan. Perintah pertama dan kedua menetapkan prinsip monoteisme dan menentang penyembahan berhala. Kedua perintah itu berbunyi sebagai berikut: “Janganlah ada Tuhan-Tuhan lain di hadapan-Ku” dan “Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air. Janganlah sujud menyembah kepadanya, karena Aku, Tuhanmu adalah Tuhan yang pencemburu” (Keluaran 20:3-5).
Doktrin paling esensial dan sistem kepercayaan yang dianut dan diperjuangkan Nabi Musa AS adalah monoteisme. Ia melan- jutkan tradisi monoteistik yang diajarkan Nabi Ibrahim AS. Baginya, Tuhan adalah satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Namun sepeninggal Musa AS, takhayul dan pemujaan berhala semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga penyembahan Yahweh dirusak oleh penyembahan Baal-Baal Funisia dan Kanaan, termasuk di dalamnya konsep „Uzair sebagai anak Allah. Karenanya sejak abad ke-9 SM, agama Yahudi sangat membutuhkan pembaruan keagamaan dari dalam. Fenomena sosial-keagamaan ini direkam Al-Qur‟an melalui ayat berikut ini:
“Orang-orang Yahudi berkata: „Uzair itu putera Allah... ” (QS. al-Taubah:30).
Ringkasnya, monoteisme Yahudi adalah monoteisme tran- senden dan etis. Tuhan bukan hanya satu dan transenden, tetapi Dia berhubungan pula dengan manusia; hubungan-Nya dengan manusia adalah hubungan etis. Sayangnya, gangguan politeistik dan asosianistik (syirik) datang menerjang berulang kali sehingga menodai kemurnian doktrin tauhidnya (Noer, 2002:189-201).
2. Kristen
Secara kronologis, Kristen muncul setelah Yahudi dan sebelum Islam. Pertumbuhan Kristen dapat dipandang sebagai perkem- bangan suatu sekte Yahudi yang menjadi sebuah agama dunia. Asal- usul Kristen tidak mungkin dipahami tanpa menempatkan agama dan kebudayaan Yahudi sebagai latar belakangnya. Dapat dikatakan bahwa orang Kristen pada awalnya adalah bangsa Yahudi sepenuhnya. Namun kristen, tanpa kehilangan ciri-ciri asal Yahudinya, secara berangsur-angsur melepaskan diri dari Yahudi dan memperoleh penganut yang sebagian besar adalah orang-orang bukan bangsa Yahudi dan tersebar di luar tanah asalnya (Bell, 1968).
Istilah “Kristen” atau “Kristenitas” berasal dari kata Yunani Christos sebagai terjemahan istilah Ibrani Mesias, yang digunakan orang Yahudi untuk menunjuk penyelamat agung mereka. Kemudian istilah Mesias (yang diterjemahkan dengan “al-Masih” atau “Kristen”) digunakan untuk menyebut Yesus dari Nasaret (Isa dari Nasirah [al- Nashirah]). Karena Yesus berasal dari Nasaret Palestina, maka ia digelari Nasrani (Nashrani) dan agama yang dibawanya disebut Nasraniah atau agama Nasrani (al-Nashra-niyyah). Kristen adalah agama orang yang mengaku percaya kepada dan mengikuti Yesus Kristus (Isa al-Masih).
Agama ini berkembang dari kehidupan dan karya Yesus dari Nasaret. Yesus Kristus bukan hanya tokoh sentral dalam Kristen, tetapi juga pusat dari keseluruhan bangunannya. Ia memilih 12 (dua belas) murid, yang kemudian disebut sebagai “al-Hawariyyun”, untuk menjalankan tugas dakwahnya. Yesus menjadi terkenal karena mukjizat, kefasihan dalam menyampaikan ajaran, dan keakrabannya dengan rakyat jelata. Namun di pihak lain, timbul rasa permusuhan dari beberapa kalangan umat Yahudi dan kecurigaan dari rezim Romawi, yang berujung pada tragedi penyaliban Yesus di pinggiran kota Yerussalem.
Terkait dengan peristiwa penyaliban ini, Islam menyangkal bahwa Yesus (baca: Isa) telah meninggal di tiang salib. Menurut Al-
Qur‟an, murid Yesus yang berkhianat, Yudas, itulah yang disalib setelah wajahnya diserupakan oleh Allah dengan wajah gurunya.
“Mereka mengatakan: Sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih, „Isa putera Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya. Tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan „Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) „Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu „Isa. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat „Isa ke sisi-Nya. Sungguh Allah Maha Perkasa laga Maha Bijaksana ” (Q.S. al- Nisa’:157-158).
Yesus, sebagaimana Nabi Musa AS, meneruskan ajaran monoteisme murni. Ketika seorang ahli Taurat datang kepada Yesus untuk menanyakan hukum yang paling utama, ia menjawab, “Hukum yang paling utama adalah: Dengarlah, wahai orang Israil, Tuhan itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yang Esa” (Mar-kus:12:29). Kalimat ini sama bunyinya dengan kalimat “Syema” (Syahadat) Yahudi, yang diucapkan oleh Nabi Musa AS kepada bangsa Israil (Ulangan 6:4).
Kristen memang agama monoteistik, tetapi konsep keesaan Tuhan tidak begitu ditekankan oleh Kristen, seperti dua agama Semitik lainnya. Karena itu, konsep tentang keesaan Tuhan bukan unsur dominan dalam Kristen. Kristen lebih mementingkan doktrin Trinitas daripada ajaran tauhid. Tuhan menginkarnasi sebagai manusia dan menebus dunia. Tuhan turun dalam suatu entitas (wujud) untuk menertibkan kembali keseimbangan dunia yang terganggu.
Dalam konteks ini perlu dicatat, otoritas gereja sendiri masih menghadapi pertentangan-pertentangan intern teologis, khususnya terkait dengan pribadi Kristus. Persoalan tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut: Siapakah Yesus Kristus sesungguhnya? Apakah ia manusia atau Tuhan? Apakah ia manusia dan Tuhan sekaligus? Atau, apakah ia manusia yang hampir sederajat dengan Tuhan? Dan, meskipun mempunyai derajat yang mulia dan melebihi manusia-manusia lain, apakah ia manusia biasa yang diciptakan Tuhan seperti manusia-manusia biasa lain?
Secara tegas, Al-Qur‟an menyatakan kesesatan teologi Trinitas Kristen ini lewat ayat berikut:
“Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan: Bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa” (Q.S. al-Maidah:73).
3. Islam, Agama Lama yang Baru
Meskipun Islam dibawa Muhammad SAW sebagai nabi terakhir atau “Penutup Nabi-Nabi” (Khatam al-Nabiyyin), agama ini tidak memandang dirinya sebagai agama baru, tetapi sebagai agama tertua. Memang jika dilihat dari perjalanan sejarah agama-agama Semitik atau Ibrahimiah, Islam adalah agama baru. Namun, bila dilihat dari esensi pesan semua nabi (tauhid yang diwahyukan Tuhan kepada mereka), maka Islam adalah agama tertua yang telah ada sejak Nabi Adam AS. Islam mengidentikkan dirinya dengan agama primordial (al-din al-hanif = agama yang benar), yaitu agama Ibrahim dan keturunannya, dan semua nabi yang diutus Tuhan kepada bangsa- bangsa Semitik, termasuk orang Ibrani dan orang Arab.
Islam memandang Yahudi dan Kristen bukan sebagai “agama- agama lain”, tetapi sebagai dirinya sendiri sejauh bersumber dari wahyu-wahyu Allah SWT kepada nabi-nabi kedua agama itu. Identisikasi diri seperti ini bukan berarti Islam tidak kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan dari jalan lurus kehendak Ilahi. Karena itu, meskipun mengidentikkan dirinya dengan Yahudi dan Kristen, Islam menyalahkan dan mengoreksi manifestasi-mani-festasi historis dari keduanya (al-Faruqi, 1986).
Islam mengakui Tuhan Yahudi dan Kristen sebagai Tuhannya sendiri dan mengakui nabi-nabi kedua agama ini sebagai nabi- nabinya sendiri. Islam mengakui bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen mempunyai komunitas-komunitas agama yang memiliki kitab-kitab suci yang diwahyukan dan menyebut mereka Ahli Kitab (Ahl al-Kitab). Islam menekankan kembali ide-ide Yahudi dan Kristen tentang keabadian pribadi (immortalitas personal), kebangkitan jasad, hari pengadilan, dan kekekalan balasan baik di surga maupun di neraka. Islam memandang Yerussalem, tempat suci kedua agama ini, sebagai tempat sucinya sendiri. Namun, Islam
mendirikan institusi baru, yaitu shalat lima kali sehari, kewajiban berzakat, dan pembacaan harian kitab suci Al-Qur‟an.
Secara teologis, Islam lebih dekat dengan Yahudi daripada dengan Kristen. Sebagaimana Yahudi, Islam sangat menekankan keesaan Tuhan dan hubungan langsung manusia dengan Tuhan. Menurut Stephen M. Wylen, seorang rabi (sarjana dan guru agama Yahudi) di Amerika Serikat, orang Yahudi mengakui bahwa ide Islam tentang Tuhan yang Esa tidak berbeda secara esensial dengan ide Yahudi tentang Tuhan. Namun ide Kristen tentang Tuhan yang Tritunggal (baca: Trinitas) sulit dipahami orang Yahudi dan penganut Islam. Orang Yahudi memandang bahwa monoteisme Islam tidak berbeda secara esensial dengan monoteisme Yahudi, tetapi mereka menolak monoteisme Kristen.
Kemodernan Islam akan tampak jika dibandingkan dengan penekanan Yahudi dan Kristen pada konsep Tuhan dan manusia. Yahudi memberikan penekanan pada konsep bahwa Tuhan adalah “Sumber Hukum” dan Hakim bangsa-Nya, sementara manusia lebih dipandang sebagai kolektivitas dan masyarakat sebagai individu- individu. Sesuai dengan penekanan ini, Yahudi memberikan penekanan pada aspek kemasyarakatan, hukum, dan keadilan. Kristen memberikan penekanan pada konsep bahwa Tuhan adalah “Sumber Kasih” yang mencintai hamba dan putera-Nya. Kristen memang mulai muncul sebagai agama mistis individual yang sangat kuat. Sesuai dengan penekanan ini, Kristen memberikan penekanan pada aspek spiritual, kebaktian, dan kecintaan dari individu-individu. Singkatnya, Yahudi memberikan penekanan pada aspek “eksoteris” (lahiriah), sedangkan Kristen memberikan penekanan pada aspek “esoteris” (batiniah).
Islam memadukan kedua sikap ini ke dalam suatu keutuhan sintesis yang tunggal. Tuhan, menurut Islam, adalah Maha Kuasa, Sang Penghukum, Hakim Yang Adil (seperti Tuhan orang-orang Yahudi), dan sekaligus Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Pemaaf (seperti Tuhan orang-orang Kristen). Islam menekankan kesatuan dan keharmonisan antara kehidupan sosial dan kehidupan individual, antara eksoterisme (lahiriah) dan esoterisme (batiniah). Dengan demikian, Islam memulihkan kembali keseimbangan sempurna antara eksoterisme dan esoterisme yang dimiliki oleh monoteisme murni yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim AS (Bleeker, 1985).
Daftar Pustaka
Al-Faruqi, Ismail R. Dan Lois Lamya‟ al-Faruqi. 1986. The Cultural Atlas of Islam. New York & London: Macmillan.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1996. Tauhidullah dan Fenomena Kemusyrikan, diterjemahkan dari Haqiqah al-Tauhid. Surabaya: Pustaka Progressif.
Allouche, Adel. 1987. “Arabian Religions,” The Encyclopedia of Religion, XVI. New York & London: Macmillan.
Bell, Richard. 1968. The Origins of Islam in its Christian Environment. London: Frank Cass & Co. Ltd.
Bleeker, C.J. 1985. Pertemuan Agama-Agama Dunia, terj. Barus Siregar. Bandung: Sumur Bandung.
Madjid, Nurcholish. Masyarakat Religius. Jakarta: Paramadina, 1997.
Noer, Kautsar Azhari. 2002. “Tradisi Monoteis,” Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Sunarso, Ali. 2009. Islam Praparadigma, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Senin, 04 April 2022
Budaya Ramadhan 1 | Ke-Otentikan Islam
A. Karakteristik Akidah Islam
Agama Islam, sebagai sistem ajaran yang sempurna (al-din al- kamil), memiliki sederet keunggulan dan kekhasan, antara lain:
1. Agama Fitrah
Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia. Siapa pun yang mengamalkan Islam dengan penuh ketaatan, kepasrahan dan ketulusan, niscaya akan mene- mukan kedamaian dan memperoleh kemuliaan. Tidak sedikit pun ajaran Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanu-siaan. Tidak pula membebani dan memberatkan manusia. Bahkan jika diperhatikan, semua hukum yang disyariatkan oleh Allah justru menopang fitrah dan kebutuhan dasar manusia.
Hal itu dibuktikan dengan substansi maqasid al-syari’ah yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengamalkan ajaran-Nya demi kesejahteraan manusia itu sendiri agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat, bukan sebaliknya untuk memberi beban berat.
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” (Q.S. al-Baqarah:286).
2. Berifat Universal
Perjumpaan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya sekitarnya, tidaklah dilakukan dengan cara konfrontasi melainkan dengan jalan akomodasi kreatif. Pengetahuan yang dikembangkan dalam ajaran Islam pun merupakan serapan dari warisan intelektual peradaban sebelumnya. Kemudian peradaban itu disajikan kembali menjadi warisan dunia yang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia.
Universalitas ajaran Islam telah dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Q.S. al-Anbiya‟:107.
“Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta.”
3. Melanjutkan Tradisi Tauhid
Tauhid merupakan urat nadi dan tujuan utama agama Islam. Dengan tauhid, manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa yang tertuang dalam Q.S. al-Baqarah:201.
“Di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".
Konsep Islam sebagai agama tauhid merupakan mata rantai ajaran sepanjang sejarah manusia dari para nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, dan Isa sampai Muhammad SAW, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. al- Anbiya‟:25.
4. Menyempurnakan Agama yang Terdahulu
Sebelum Islam datang, telah ada banyak agama di dunia ini, baik agama yang masuk katagori samawi (agama langit) maupun ardhi (agama bumi). Di antara agama-agama itu adalah agama bangsa Kildean (Mesopotamia), agama bangsa Mesir, Hindu dan Budha (India), Zoroaster atau Majusi (Persia Iran), Tao atau Kong Hu Chu (Tiongkok), Shinto (Jepang), Nasrani (Palestina), dan Yahudi (Israel). Namun agama-agama tersebut memiliki berbagai keterbatasan.
Pertama, agama-agama sebelum Islam hanya diperuntukkan bagi umat tertentu. Misalnya, agama Yahudi dan Nasrani hanya diperuntukkan bagi Bani Israil seperti dinyatakan dalam Mathius
15:24, “Maka jawab Yesus. Katanya: Tiadalah aku disuruh kepada yang lain, hanya kepada segala domba yang sesat di antara Bani Israil”. Sedangkan Islam mempunyai visi universal sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Anbiya‟:107.
Kedua, ajaran-ajaran Tuhan yang terdapat dalam agama sebelum Islam sudah dipalsukan oleh para tokoh pemuka agama- agama itu. Misalnya, Taurat (Perjanjian Lama) dan Injil (Perjanjian Baru), saat ini tidak ada yang asli. Bahkan seandainya isi Injil Lukas, Mathius, Markus, Yohanes, dan Paulus dibandingkan, maka akan ditemukan perbedaan yang prinsipil. Sedangkan agama Islam tidak akan pernah dipalsukan, karena al-Qur‟an sebagai sumber ajaran dijamin otentisitasnya oleh Allah SWT.
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” (Q.S. al-Hijr:9)
5. Mendorong Kemajuan
Kemajuan peradaban manusia akan terwujud apabila manusia mampu memanfaatkan potensi akalnya dengan baik. Misi tauhid adalah membebaskan manusia dari penjara mitos, tahayul, dan penghambaan kepada ciptaan Allah yang hakikatnya lebih rendah martabatnya. Alam dengan segala isinya diciptakan untuk diman- faatkan, bukan untuk disakralkan. Ini merupakan paradigma yang sangat revolusioner dalam sejarah umat manusia.
Banyak sekali ayat al-Qur‟an yang menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Islam mengajarkan bahwa hukum- hukum Allah (sunnatullah) dalam kehidupan ini ada dua macam, yaitu yang tertulis (qauliyah) dan yang tidak tertulis (kauniyah). Sunnah qauliyah adalah hukum yang diwahyukan kepada para nabi. Sedangkan sunnah kauniyah ialah ketentuan yang tidak diwah- yukan, seperti suhu udara, tata surya, panas matahari, iklim, derajat panas air, hukum titik cair baja, gravitasi, dan sebagainya. Hal itu dimaksudkan agar manusia melakukan penelitian dan memikirkan betapa dahsyat ciptaan-Nya.
“Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman" (Q.S. Yunus:101).
Manusia dalam pandangan Islam merupakan makhluk merdeka dan bebas menentukan kehidupannya. Allah telah menganugerahkan potensi kebaikan dan kejelekan dalam diri manusia. Semua perbuatannya di dunia akan dipertanggungjawabkan sendiri secara individual di hadapan-nya. Ini berarti bahwa kebebasan yang dimaksud bukan “kebebasan absolut” sebagaimana dipahami oleh aliran Qadariyah (free will), dan bukan pula “kebebasan nihil” seperti dipahami sekte Jabbariyah (fatalism). Islam hadir dengan “wajah tengah” di antara dua aliran tersebut. “Kebebasan ber-imbang” yang nantinya memunculkan potensi kreatif (creative force) dalam diri manusia itulah yang dikehendaki oleh al-Qur‟an.
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri” (Q.S. al-Ra’d:11).
Sebagai bukti konkrit, Islam mendorong kemajuan adalah bahwa syariat tidak mengatur secara rinci (tafsili) hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Asalkan tidak melanggar tuntunan syara‟, Islam mendukungnya. Ayat-ayat al-Qur‟an yang berkenaan dengan persoalan muamalah hanya memberikan ketentuan secara garis besar (ijmali) karena memang kehidupan terus berkembang secara dinamis.
Mahasiswa PLB Universitas Negeri Malang Tanamkan Nilai Anti Korupsi Sejak Dini di SDN Lowokwaru 5
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM : Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas Negeri Malang melaksanakan kegiatan Sosialis...

-
Bencana kerap menjadi momentum bagi sebagian orang/ kelompok/ komunitas/ organisasi/ lembaga atau bahkan mahasiswa untuk bahu-membahu memban...
-
Gondanglegi, Madrasah Aliyah Negeri 1 Malang (MAN 1 MALANG) kembali menggelar Sholawat Rutin yang telah lama dilaksanakan setiap jum'at ...
-
Berbicara organisasi, untuk membicarakannya akan dibingungkan oleh mengawalinya, membicarakan organisasi tak semudah mendefinisikan apa itu ...